KATA
PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkn kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan nikmat, ilmu dan amal, sehingga tugas ini dapat diselesaikan . Tugas ini merupakan
tugas tentang Laporan Hasil Membaca Buku Karangan Prof. Dr. H. Mohamad Surya. Pembuatan
tugas ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi
Pembelajaran Matematika pada semester ganjil. Bukan hanya laporan buku tetapi
penulis harus mengimplementasikan topik yang dipilih dalam pembelajaran
matematika.
Adapun judul buku yang dipilih adalah Strategi Kognitif dalam
Pembelajaran karangan Prof. Dr. H. Mohamad Surya. Semoga laporan buku dan
implementasi yang penulis buat dapat bemanfaat baik bagi penulis sendiri maupun
bagi pembaca. Walaupun tulisan ini masih banyak kekurangan tetapi semoga
menambah wawasan pembaca dan pembaca menjadi tertarik untuk membaca bukunya.
Penulis
Yulia Nursari
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan
Laporan buku yang penulis susun adalah laporan buku
Non-Fiksi yaitu buku yang berjudul Strategi Kognitif dalam Pembelajaran.
Laporan buku ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pembelajaran
Matematika pada semester I. Selain membuat laporan buku, tugas yang diberikan
adalah bagaimana implementasi dari topik yang dipilih pada pembelajaran
matematika.
Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi
Pembelajaran Matematika, penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan mengenai salah satu topik yang dipilih dari buku Strategi Kognitif
Pembelajaran dan gambaran sekilas mengenai buku dan pengarangnya.
B.
Identitas
Judul Buku : Strategi Kognitif dalam Pembelajaran
Pengarang : Prof. Dr. H. Mohamad Surya
Penerbit : ALFABETA BANDUNG
Tahun Terbit : 2016
Ukuran Dimensi Buku :
16
Tebal Buku : 232 halaman
Format Perwajahan : 1. Warna
dasar cover depan berwarna hitam dan bergambar papan catur dan puzzel , judul buku berwarna putih, serta nama pengarang ditulis dibagian atas
buku berwarna putih.
2. Warna dasar cover belakang berwarna hitam
dan bergambar papan catur dilengkapi gambaran umum
mengenai isi buku tersebut serta terdapat nama penerbit di
bagian bawah cover.
C.
Kepengarangan
Prof. Dr. H. Mohamad
Surya (lahir di Kuningan, Jawa Barat, 8 September 1941; umur 76 tahun) adalah akademisi dan pengajarIndonesia. Ia
pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI)
periode 1998-2003 dan periode 2003-2008. Selain itu, juga menjadi salah seorang dari empat
orang wakil asal provinsi Jawa Barat yang
menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2004-2009.
Mohamad Surya adalah
putera dari Sastrasantana, yang juga seorang guru. Pendidikan yang
diikutinya dimulai dari SD Citangtu Kuningan (lulus tahun 1954), kemudian SGA/KGA (1962), sarjana muda IKIP Bandung (1965), dan sarjana pendidikan IKIP Bandung(1968). Gelar doktor pendidikan
diraihnya tahun 1979, juga dari IKIP Bandung setelah
mempertahankan disertasi mengenai faktor non-intelektif pada siswa berprestasi
kurang. Selain itu, ia juga mengikuti program refreshing di Ohio State University (1987) dan program
Internship di Indiana
University (1989).
Kariernya sebagai Guru diawali
dengan menjadi pengajar Sekolah Rakyat (sekarang SD) di Kuningan (1958-1962). Kemudian
menjadi guru SPG-B/SMA di Bandung (1966-1973). Mulai
tahun 1966, ia menjadi dosen di Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI), dan
menyandang jabatan sebagai guru besar sejak
tahun 1997.
Keterlibatan
di PGRI sudah dilakukannya sejak tahun 1958, sebagai anggota ataupun sebagai
pengurus. Sedangkan jabatan sebagai ketua umum organisasi ini, terakhir
diperolehnya saat terpilih untuk kedua kalinya tanggal 12 Juli 2003 dalam
Kongres ke XIX PGRI yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.
.
BAB
II
LAPORAN
ISI BUKU
A.
Latar Belakang Pemilihan Topik
Saat ini pemerintah memberlakukan
kurikulum 2013 dimana pada kurikulum 2013 ini diharapkan
dapat diimplementasikan pembelajaran
abad 21. Penerapan pemelajaran abad 21 pada kurikulum 2013 ini untuk
menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif.
Menurut Rudi
Mustafa dalam sebuah postingan pada 22 Mei 2017 menyatakan sebagai berikut
ini.
Pembelajaran yang
berpusat pada peserta didik berbeda dengan pembelajaran yang berpusat pada
pendidik/guru, berikut karakter pembelajaran abad 21 yang sering disebut
sebagai 4 C, yaitu:
Communication (Komunikasi)
Pada karakter ini,
peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi
yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan
multimedia. Peserta didik diberikan kesempatan menggunakan kemampuannya untuk
mengutarakan ide-idenya, baik itu pada saat berdiskusi dengan teman-temannya
maupun ketika menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pendidik.
Collaboration (Kerjasama)
Pada karakter ini,
peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan
kepemimpinan; beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab; bekerja
secara produktif dengan yang lain; menempatkan empati pada tempatnya;
menghormati perspektif berbeda. Peserta didik juga menjalankan tanggungjawab
pribadi dan fleksibitas secara pribadi, pada tempat kerja, dan hubungan masyarakat;
menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan
orang lain.
Critical
Thinking and Problem Solving (Berpikir Kritis
dan Pemecahan Masalah)
Pada karakter ini,
peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam
memahami dan membuat pilihan yang rumit; memahami interkoneksi antara sistem.
Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, peserta didik juga
memiliki kemampuan untuk menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan
menyelesaikan masalah.
Creativity and
Innovation (Daya cipta dan Inovasi)
Pada karakter ini,
peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan
menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain; bersikap terbuka dan
responsif terhadap perspektif baru dan berbeda.
Sehingga pada abad 21 saat ini yang bisa disebut sebagai
era pengetahuan, maka tujuan pendidikannya pun adalah:
1) mempersiapkan
orang dalam dunia pasang surut, dinamis, unpredictable (tidak
bisa
diramalkan),
2) perilaku yang
kreatif,
3) membebaskan
kecerdasan individu yang unik, serta
4) menghasilkan
inovator.
Dengan demikian,
model sekolah pada abad ini mengharapkan pendidikan dapat menjadikan
individu-individu yang mandiri, sebagai pelajar yang mandiri.
Salah satu ciri
pembelajaran abad 21 adalah Critical
Thinking Dan Problem Solving.
Dalam ciri ini
mengimplikasikan bahwa siswa harus memiliki kemampuan berfikir diantaranya:
kreatif, berfikir kritis, pemecahan masalah,
pengambilan keputusan dan pembelajar. Bukan hanya siswa yang dituntut untuk
berpikir kritis dan kreatif serta inovatif tetapi guru pun demikian.
Untuk lebih
memahami apa dan bagaimana cara berfikir serta penerapannya dalam pendidikan
khususnya dalam pembelajaran matematika maka penulis mengambil salah satu topik
dari salah satu buku karangan Prof. Dr. H. Mohamad Surya yang berjudul Strategi Kognitif dalam Pembelajaran. Topik terseut adalah “BERPIKIR” yang merupakan judul dari BAB IX
halaman 117-136.
B.
Isi Buku (Bab IX “BERPIKIR”)
1.
Pengertian
dan Proses berpikir
Berpikir
adalah perilaku kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi atau tertinggi yang
merupakan bentuk pengenalan dengan memanipulasi sejumlah konsep terutama dalam
tatanan konsep abstrak. Oleh karena itu kemampuan berpikir hanya mungkin dapat
dilakukan apabila telah memiliki konsep-konsep tertentu dengan ditunjang daya
nalar yang kuat.
Poses
berpikir berlangsung melalui moda-moda kognitif yang meliputi pengamatan,
ingatan, pembentukan konsep, pemberian respons, menganalisis, memandingkan,
imajinasi, dan penimbangan (judging).
Moda-moda kognitif didukung oleh delapan unsur berikut:
a.
Tindakan yang dilakukan dengan satu
tujuan yang disadari.
b.
Dilakukan berdasarkan sudut pandang
tertentu.
c.
Berbasis suatu asumsi tetentu secara
disadari.
d.
Mengarah kepada satu langkah pelaksanaan
dengan kesiapan menghadapi konsekuensi tertentu.
e.
Dilaksanakan dengan menggunakan berbagai
informasi dan pengalaman.
f.
Dilakukan dengan menggunakan perkiraan
dan timbangan yang berbasis nilai-nilai tertentu.
g.
Menggunakan daya nalar yang baik, sehat,
dan ojektif.
h.
Semua tindakan dilakukan dalam upaya
memperoleh jawaban satu pertanyaan tertentu.
Menurut
para ahli berpikir dikategorikan menjadi dua yaitu berpikir dengan otak kiri dan berpikir dengan otak kanan.
Dari
sudut arah berpikir dibedakan antara convergent
thinking (berpikir memusat) yaitu berpikir yang terpusat pada satu
aktivitas dan sasaran, dan divergent
thinking (berpikir menyebar) yaitu berpikir secara menyebar. Convergent
thinking lebih bersifat ke kiri dengan karakteristik lebih terarah, lebih
eksplisit, dapat berfokus pada satu sasaran. Divergent thinking lebih bersifat
ke kanan dengan karakteristik lebih bersifat ke kanan dengan karakteristik
menunda timbangan, mencari dan menerima lebih banyak gagasan membangun gagasan,
dapat keluar dari rel rancangan. Tugas
guru harus mampu berpikir dengan seimbang antara otak kiri dan otak kanan serta
menjaga keseimbangan antara berpikir konvergen dan divergen.
Berpikir kritis
lebih bersifat ke kiri dengan fokus menganalisis dan mengembangkan berbagai
kemungkinan. Berpikir kreatif lebih
ersifat ke kanan dengan fokus membuat dan mengomunikasikan hubungan baru yang
lebih bermakna.
2.
Perkembangan
Berpikir
Perkembangan
berpikir (kognitif) merupakan salah satu aspek perkembangan mental yang
bertujuan untuk :
a.
Memisahkan kenyataan yang sebenarnya
dengan fantasi;
b.
Menjelajah kenyataan dan menentukan
hukum-hukumnya;
c.
Memilih kenyataan-kenyataan yang berguna bagi
kehidupan;
d.
Menentukan kenyataan yang sesungguhnya
dibalik sesuatu yang nampak.
Menurut
Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses perkembangan kemajuan
individu melalui suatu rangkaian yang secara kualitatif berbeda dalam
berpikir.Perkembangan kognitif terbentuk melalui interaksi yang konstan antara
individu dan lingkungannya yyang dikendalikan oleh adanya prinsip keseimbangan.
Dari interaksi dengan lingkungan individu
akan memperoleh pengetahuan dengan menggunakan asimilasi, akomodasi, dan
dikendalikan oleh prinsip keseimbangan.
Pekembangan
kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi sehingga dewasa,
yang berlangsung melalui empat peringkat seperti berikut ini.
Peringkat sensori-motor (0 – 1,5 tahun),
aktivitas kogniti berpusat pada aspek alat dari sensori dan gerak;
preoperasional (1,5 – 6 tahun), anak telah mampu menunjukan aktivitas kognitif
dalam menghadapi berbagai hai di luar
dirinya, congcrete operational ( 6 – 12 tahun), anak telah dapat membuat pemikiran
tentang situasi atau kongkrit secara logis; fomal operational (12 tahun ke
atas), perkemangan kognitif ditandai dengan kemampuan individu untuk berpikir secara hipotesis dan berbeda dengan
fakta, memahami konsep abstrak, dan kemampuan mempertimbangkan kemungkinan
cakupan ang luas dari hal-hal yang terbatas.
Proses
pembelajaran akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan peringkat
perkembangan kognitif siswa.
Implikasi
teori perkembangan kognitif Piaget dalam pengajaran, antara lain sebagai
berikut ini.
a.
Bahasa dan cara berpikir anak berbeda
dengan orang dewasa, maka pada saat mengajar guru menggunakan bahasa yang
sesuai dengan cara berpikir anak.
b.
Anak-anak akan belajar lebih baik apabila
dapat menghadapi lingkungan dengan baik
c.
Bahan yang harus dipelajari anak
hendaknya dirasakan baru tapi tidak asing.
d.
Beri peluang anak belajar sesuai dengan
peringkat perkembangannya.
e.
Di dalam kelas, anak-anak hendaknya banyak dieri peluang
untuk saling berbicara dengan teman-temannya dan saling erdiskusi.
3.
Bepikir
kritis
Berpikir
kritis merupakan salah satu strategi kognitif dalam pemecahan masalah yang
lebih kompleks dan menuntut pola yang lebih tinggi. Berpikir kritis lebih anak
berada dalam kendali otak kiri dengan fokus pada menganalisis dan mengembangkan
berbagai kemungkinan dari masalah yang dihadapi. Berpikir kritis yaitu berpikir
untuk:
a.
Membandingkan dan mempertentangkan
berbagai gagasan;
b.
Memperbaiki dan memperhalus;
c.
Bertanya dan verifikasi;
d.
Menyaring, memilih dan mendukung gagasan;
e.
Membuat keputusan dan timbangan;
f.
Menyediakan landasan untuk suatu
tindakan.
Deinisi-definisi berpikir kritis :
a.
Satu pola berpikir reflektif yang berfokus
pada pembuatan keputusan tentang apa yang diyakini atau yang dilakukan (Ennis,
1987, dalam Bruning, 2012)
b.
Berpikir kritis adalah berpikir yang
lebih baik (Perkins, 2001, dalam Bruning, 2012)
c.
Berpikir ang membedakan antara berpikir
yang diarahkan mendapatkan tujuan dengan mengklarifikasi tujuan (Nickerson,
1987 dalam Bruning 2012).
4.
Keterampilan-keteampilan
dalam Berpikir Kritis
Ada
dua faktor penting yang menunjang kecakapan berpikir kritis yaitu disposisi
dan kecakapan.
Komponen utama berpikir
kritis adalah pengetahuan. Pengetahuan
merupakan sesuatu yang digunakan untuk berpikir secara kritis dan juga
diperoleh sebagai hasil berpikir kritis.
Pengetahuan dalam bentuk strategi secaa
akti akan mementuk arahan dalam pemecahan masalah. Hal penting lainnya aitu
infefensi atau membuat kesimpulan dalam proses berpikir kritis. Terdapat empat
macam inferensi aitu deduksi, induksi, evaluasi, dan metakognisi.
Selanjutnya
, Ennis (1987 dalam Bruning, 2014) menyatakan ada dua belas keterampilan yang
diperlukan dalam proses berpikir kritis secara efektif seperti berikut ini.
a.
Memfokuskan pada pertanyaan.
b.
Menganalisis argument;
c.
Menanyakan dan menjawab pertanyaan
klarifikasi.
d.
Menimbang kredibilitas suatu sumber;
e.
Mengamati dan menimang laporan hasil
pengamatan;
f.
Menimbang deduksi;
g.
Menimbang induksi;
h.
Membuat timbangan nilai
i.
Meumuskan istilah dan menimbang definisi;
j.
Mengidentifikasi asumsi;
k.
Memutuskan suatu tindakan.
l.
Berinteaksi dengan orang lain.
5.
Perencanaan
Program Keterampilan Bepikir Kritis
Terdapat
dua kategoi yang dirancang untuk memperbaiki keterampilan bepikir yaitu
Stand-alone programs dan Embedded programs.
Tedapat
tiga tahapan pengembangan pogram keteampilan berpikir kritis.
a.
Identifikasi keterampilan yang tepat
Terdapat
dua model program keterampilan berpikir kritis yaitu model deskriptif, yang
menjelaskan bagaimana berpikir terjadi secara aktual dan model preskriptif,
yang menjelaskan bagaimana keterampilan berpikir yang baik seharusnya terjadi.
b.
Menerapkan pengajaran
Agar
program dapat berjalan dengan efektif, para pengajar harus menyajikan
keterampilan berpikir dalam urutan yang jelas dan bemakna, yang meliputi: (1)
pengembangan hipotesi mengenai sebab-sebab suatu peristiwa; (2) membangun
aturan untuk menata bukti-bukti yang diterima; (3) mengumpulkan bukti-bukti
baik dari sumber eksternal maupun internal; (4) menguji reliabilitas bukti; dan
(5) menilai sebab-sebab yang berbeda.
c.
Menilai program.
Untuk
mengetahui keefektifan program, langkah penting yang harus dilakukan yaitu
menilai program sejak program mulai dirancang, selama implementasi, dan setelah
program diterapkan.
6.
Berpikir
Ilmiah
Pola
berpikir yang dipergunakan dalam menghasilkan suatu kara ilmiah merupakan pola
berpikir reflektif, yaitu pola berpikir dengan prosedur yang dilakukan melalui
aktivitas mengadakan refleksi secara logis dan sistematis diantara kebenaran
ilmiah dan kenyataan empiris dalam mencari jawaban terhadap suatu masalah. Cara
berpikir reflektif mengandung proses berpikir induktif dan deduktif secara
terpadu yang mendasari keseluruhan proses bepikir.
Terdapat
tiga aspek yang diperlukan dalam menjuruskan ke dalam berpikir ilmiah, yaitu sebagai berikut :
a.
Penjelasan Ilmiah
Cara
memberikan penjelasan dapat dilakukan dengan : (1) memberikan nama atau simbol
terhadap pokok pikiran yang akan dijelaskan, (2) penjelasan secara historis
yaitu suatu pikiran dengan menghubungkan kepada kenyataan-kenyataan sebelumnya
secara logis; (3) penjelasan dengan korelasi empiris yaitu memberikan
penjelasan suatu pikiran dengan menghubungkan dengan pikiran lain yang terjadi
bersamaan secaa logis. Dilihat dari sifatnya, penjelasan ilmiah dapat berupa
penjelasan deskriptif, induktif, atau deduktif.
b.
Pengertian Operasional
Membuat
pengertian operasional dapat dilakukan dengan membuat definisi atau sinonim dari hal-hal yang akan dijelaskan.
c.
Berpikir Kuantitatif
Untuk
lebih menjamin ojektivitas penyampaian pikiran atau keterangan, maka diperlukan
adanya proses kuantifikasi informasi
yang diperoleh, dan ini menunjukkan
perlunya
data kuantitatif sebagai pendukung terhadap segala sesuatu pikirran yang akan
dikemukakan.
BAB
III
Implementasi dari Bab IX (Berpikir) dalam Pembelajaran
Matematika
A.
Mengembangkan
Otak Kiri dan Otak Kanan Secara Seimbang
Dari uraian mengenai pembelajaran abad 21, yang sering
disebut dengan 4C sangat diperlukan kreativitas dari guru. Dalam buku Strategi Kognitif dalam Pembelajaran karangan Prof. Dr. H.
Mohamad Surya halaman 119 dinyatakan bahwa Tugas
guru harus mampu berpikir dengan seimbang antara otak kiri dan otak kanan serta
menjaga keseimbangan antara berpikir konvergen dan divergen, untuk selanjutnya
membimbing siswa agar mampu berpikir secara efektif dalam keseimbangan.
Pernyataan Prof. Dr. H. Mohamad
Surya tersebut sangat sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21,
yaitu guru harus kreatif, inovatif dan berpikir kritis . Bagaimana supaya guru
kreatif dan inovatif maka guru harus menggunakan otak kiri dan otak kanan
secara seimbang. Guru yang kreatif,
inovatif dan berpikir kritis akan melahirkan
siswa yang berpikir kritis dan kreatif.
Menurut Prof. Dr.
H. Mohamad Surya dalam bukunya halaman119 dibedakan antara pola berpikir
kritis dan berpikir kreatif. Bepikir
kritis lebih bersifat ke kiri dengan fokus pada menganalisis dan
mengembangkan berbagai kemungkinan. Berpikir
kreatif lebih bersifat ke kanan dengan fokus membuat dan mengomunikasikan
hubungan baru yang lebih bermakna.
Untuk menerapkan
pembelajaran abad 21 yang meliputi 4C dan diantaranya memuat berpikir kritis
dan kreatif serta inovatif, guru
harus berusaha membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya memuat
kegiatan yang dapat merangsang otak kiri dan kanan siswa berkembang seimbang. Untuk merangsang otak kanan siswa pada
kegiatan pembelajaran di dalamnya
diberikan:
1) Ice breaking atau permainan
tetapi tetap dalam koridor pembelajaran. Contoh di awal atau di tengah
pembelajaran dilakukan ice breaking atau permainan matematika.
2) Memberikan Teka-Teki yang
berhubungan dengan matematika. Dengan teka-teki biasanya siswa mengerahkan
segenap pemikirannya supaya dapat menjawab teka-teki.
3) Menggunakan
media pembelajaran yang merangsang audio isual seperti Power Point, Aplikasi
Matematika, Game matematika yang merangsang penglihatan dan pendengaran siswa.
Untuk
merangsang otak kiri supaya berpikir
kritis dalam evaluasi diberikan soal-soal open ended atau yang sekarang sedang
dianjurkan dalam pembelajaran abad 21 dikenal dengan soal HOTS (Higher Order Thinking Skill). Soal-soal HOTS diberikan
pada:
1) Proses
Pembelajaran ketika siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa bersama dengan teman
sekelompoknya sehingga diantara siswa terjadi saling bertukar pikiran.
2) Setelah
proses pembelajaran yaitu diberikan sebagai pekerjaan rumah.
3) Waktu
tertentu diberikan kepada sebagian siswa yang mempunyai bakat terhadap
matematika yaitu pemberian latihan soal-soal olympiade.
B.
Menerapkan
Keterampilan Berpikir Kritis
Untuk menerapkan keterampilan berpikir kritis pada siswa
di kelas, dirancang model pemelajaran yang dapat mendorong siswa untuk
melakukan kegiatan yang memuat keterampilan berpikir kritis. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah
model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa
karena dengan model ini siswa berusaha mengeluarkan semua kemampuannya untuk
memahami masalah, mencari strategi pemecahan masalah, melaksanakan strategi
dalam menyelesaikan masalah dan meneliti kembali hasil pemecahannya. Dalam
model pembelajaran berbasis masalah ini diperlukan kerjasama antar anggota
kelompok dan ini merupakan kegiatan interaksi antara siswa yang merupakan
keterampilan yang diperlukan dalam poses berpikir kritis.
Model Pembelajaran
Discoery Learning bisa dijadikan alternatif model pembelajaran untuk
menerapkan keterampilan berpikir kritis siswa karena siswa dituntut untuk
mencari informasi dan menggunakan informasi untuk menemukan suatu konsep atau
prinsip-prinsip. Alur kegiatan yang dilakukan siswa dalam model pembelajaran
Discovery Learning merupakan keterampilan yang diperlukan dalam poses berpikir
kritis.
Model Project
Based Learning juga merupakan model pembelajaran yang lebih menantang sebab siswa selain melakukan
kegiatan di kelas juga melakukan kegiatan di luar kelas. Dengan model ini siswa
dituntut merencanakan project yang akan dibuat, menyusun langkah-langkah,
menentukan bahan-bahan yang diperlukan, menentukan jadwal atau waktu untuk
menyelesaikan project, mencari informasi di luar kelas, berkonsultasi dengan
guru ataupun dengan sumber lain di luar sekolah, sampai diperoleh hasil sesuai
rencana. Semua kegiatan dalam project based learning merupakan keterampilan
yang diperlukan dalam poses berpikir kritis.
Dalam penerapan pembelajaran abad 21 harus mengembangkan
komuikasi dan kolaboasi serta menggunakan teknologi maka digunakanlah komputer
atau aplikasi-aplikasi matematika dalam pembelajaran di kelas untuk menarik
minat siswa supaya siswa tidak merasa bosan dan monoton. Untuk hal ini maka guru
harus meningkatkan kompetensinya dalam segala bidang bukan hanya mata pelajaran
saja tetapi dalam bidang teknologi karena ciri dari pembelajaran abad 21 adalah
penggunaan TIK baik di kelas ketika tatap muka ataupun di luar kelas seperti
memberikan tugas atau latihan online.
C.
Menerapkan
Berpikir Ilmiah
Berpikir
Ilmiah dalam pembelajaran sehari-hari bisa diterapkan dengan menggunakan model
pembelajaran Discoery Learning karena dalam langkah-langkahnya memerlukan
pemikiran seperti ilmuwan. Dalam model ini siswa harus mampu menemukan konsep
ataupun prinsip-prinsip dalam matematika dan untuk menemukannya diperlukan
aspek-aspek berpikir ilmiah. Dengan model ini siswa dilatih aspek berpikir
ilmiah yaitu penjelasan ilmiah dimana siswa harus bisa menghubungkan pengetahuan
yang sudah diperoleh dengan pengetahuan baru serta siswa harus mampu
menjelaskan secara ilmiah.
Selain
menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk melatih berpikir ilmiah
siswa bisa dengan memberikan soal-soal yang memerlukan kemampuan penalaran
seperti soal pemecahan masalah.
A.
B.
DAFTAR PUSTAKA
Surya, M. (2016) Strategi
Kognitif dalam Pembelajaran. Bandung, Alfabeta
https://ainamulyana.blogspot.com › Berita › Pembelajaran







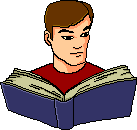
4 Komentar
Kereen ibu, terimakasih untuk ilmunya
BalasHapusAlhamdulillah kalau bermanfaat
Hapuswahh infonya menarik sekali
BalasHapusAlhamdulillah semoga bermanfaat
Hapus